DEWI MAUT JILID 040
Kalau kita bicara tentang sebab akibat, maka segala akibat apapun yang terjadi di dalam dunia menimpa diri kita adalah disebabkan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu seorang bijaksana tidak akan memandang akibat, melainkan selalu waspada dan sadar akan segala gerak-gerik dari setiap pikiran dan perbuatan dirinya sendiri lahir batin karena dari setiap pikiran dan badan itulah yang menjadi sebab dari semua akibat, yang penting adalah mengenal diri pribadi sehingga setiap detik kita dapat waspada akan semua pikiran dan sikap kita, baik gerak tubuh maupun kata-kata.
Yang penting adalah caranya, bukan tujuannya, karena tujuan tidak Akan jauh dari caranya, atau akibat tidak berbeda dengan sebabnya! Kalau caranya benar, maka akibat atau tujuan dari cara itu bukan merupakan persoalan lagi. Dan cara itu, cara hidup atau setiap gerak-gerik hati pikiran dan kata-kata perbuatan kita saat demi saat barulah benar apabila terbebas dari segala macam bentuk kekotoran yang timbul dari nafsu keinginian pribadi, dan kekotoran ini lenyap oleh kesadaran dan pengertian yang timbul pula dari pengawasan kita, pengenalan kita terhadap diri sendiri setiap saat.
Cara yang tidak benar pasti akan menjadi sebab terjadinya akibat yang tidak benar pula, ini sudah pasti, sungguhpun cara itu sudah terlupa oleh kita, sudah tersembunyi di alam bawah sadar.
Akan tetapi, pengertian ini bukan berarti bahwa kita lalu sengaja menggunakan cara yang benar untuk memperoleh akibat yang benar, kalau demikian maka cara itu sudah menjadi tidak benar karena mengandung pamrih keuntungan pribadi sehingga menjadi palsu. Kalau demikian, maka hanya akan terbentuk lingkaran setan belaka, yaitu sebab menimbulkan akibat, dan akibat menjadi sebab pula dari akibat yang lain lagi!
Inilah apa yang dinamakan hukum karma, tanpa kita buat sendiri dengan merangkaikan kemarin memasuki hari ini untuk sampai kepada esok hari! Dan ini akan berulang terus dan kita terseret di dalamnya! Oleh karena itu, yang penting adalah saat ini, sekarang ini! Setiap saat awas terhadap diri sendiri, bukan dalam arti kata menekan atau mengendalikan, hanya waspada tanpa pamrih, tanpa apa-apa, hanya waspada saja. Kewaspadaan setiap saat ini yang akan bekerja sendiri, tanpa pamrih dari si aku.
Setiap kali bencana menimpa diri kita, keluarga kita, kita akan merasa tidak adil. Kematian orang yang kita kasihi, malapetaka yang menimpa membuat kita menjadi miskin, dan sebagainya, membuat kita merasa prihatin dan sengsara. Kita tidak membuka mata bahwa mala petaka itu setiap saat memang ada, menimpa kepada siapapun juga dan selalu akan terasa ada kesengsaraan dan kedukaan selama tidak terjadi perobahan hebat di dalam batin kita. Karena kesengsaraan dan kedukaan itu timbul dari dalam pikiran kita sendiri!
Pada hari itu terjadi geger di kota Leng-kok terutama sekali di rumah Yap Kun Liong. Pendekar ini pagi-pagi sekali memasuki kota Leng-kok dan langsung dia menuju ke rumahnya.
Semenjak hari kemarin, hatinya selalu tidak enak. Hal ini tadinya disangkanya sebagai akibat kunjungannya ke Cin-ling-pai dan mendengar tentang malapetaka yang menimpa keluarga Pendekar Sakti Cia Keng Hong. Dia menghadap pendekar yang sudah dianggapnya seperti pengganti ayahnya sendiri, juga gurunya, dan dengan tegas menyatakan kesediaannya untuk pergi mencari kembali pusaka Cin-ling-pai yang hilang dan membuat perhitungan dengan Lima Bayangan Dewa.
Namun dengan tulus Cia Keng Hong menolaknya, mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa urusan itu adalah urusan keluarganya, urusan pribadi dan sekarang Cia Bun Houw sudah pergi, bersama empat orang murid kepala Cin-ling-pai, untuk melakukan tugas itu secara terpencar.
Kun Liong maklum bahwa orang tua itu sedang mengalami tekanan batin yang hebat dan menghiburpun tidak ada artinya. Maka dia tidak tinggal diam di Cin-ling-pai, lalu berpamit dan mulai saat itulah hatinya selalu terasa tidak enak. Lebih-lebih lagi malam tadi, dia gelisah sekali sehingga malam-malampun dia tidak mau berhenti dan melanjutkan perjalanan pulang ke Leng-kok.
Keadaan Cin-ling-pai membuat hatinya seperti terhimpit juga dan dia ingin lekas-lekas bertemu dengan isterinya karena di dunia ini hanya ada satu orang yang akan dapat meringankan perasaannya apabila sedang terhimpit oleh keadaan, orang itu adalah Pek Hong Ing, isterinya tercinta.
Kun Liong terkejut ketika melihat banyak orang berkumpul di rumahnya dan toko obatnya tidak dibuka seperti biasa. Matanya terbelalak bingung ketika melihat kain putih di pintu rumah, putih berkabung tanda bahwa ada yang mati. Lebih-lebih lagi ketika lapat-lapat dia mendengar suara tangis seorang wanita yang dikenalnya sebagai suara Khiu-ma!
Jantungnya seperti berhenti berdetak, kakinya seperti mendadak kehilangan tenaganya dan dia berjalan menghampiri pintu rumahnya dengan muka pucat dan kaki terhuyung. Beberapa orang tetangga yang berada di depan, begitu melihat dia kontan menangis tersedu-sedu, wanita-wanita sesenggukan dan tidak ada yang berani memandangnya.
“Ada apa...?”
Suara ini jelas keluar dari mulutnya, akan tetapi dia sendiri tidak mendengarnya, seolah-olah suaranya telah lenyap ditelah kecemasan yang mengerikan.
Dia melangkah masuk. Banyak orang di dalam dan kembali mereka ini menangis begitu melihatnya. Seorang wanita tetangga yang amat baik, seperti keluarga sendiri, menubruk kakinya, menjerit dan menangis sesenggukan tanpa bisa mengeluarkan suara.
“Ada apa...?”
Kini suara yang keluar dari tenggorokan Kun Liong terdengar keras sekali, menjerit penuh ketakutan, penuh kecemasan, penuh bayangan yang bukan-bukan.
Tidak ada seorangpun menjawab akan tetapi semua mata ditujukan ke arah kamarnya dari mana terdengar tangis Khiu-ma yang jelas sekali sekarang, diiringi suara keluh kesah seorang laki-laki yang dikenalnya sebagai suara Giam Tun.
“Apa yang terjadi...?”
Kun Liong melangkah masuk ke pintu kamarnya dan tiba-tiba dia berdiri terpaku di ambang pintu, mukanya pucat sekali seperti mayat dan matanya terbelalak memandang ke atas pembaringan di kamar itu, seolah-olah dia tidak mau percaya akan apa yang dilihatnya. Dikejap-kejapkannya matanya, lalu digosok-gosoknya dengan kepalan tangan yang gemetar, akan tetapi tetap saja pemandangan itu tidak berobah.
“Taihiap... uhhuu-hu-huuuuk...!” Giam Tun menoleh dan hanya dapat mengeluarkan seruan demikian, karena dia sudah berlutut dan menangis bergulingan diatas lantai. Khiu-ma menjerit.
“Apa ini...? Apa ini...? Bagaimana...? Kenapa...?”
Kun Liong makin terbelalak, bibirnya gemetar, banyak kata-kata yang keluar tanpa suara, lalu ditamparnya kepalanya sendiri untuk menyadarkannya dari mimpi buruk ini. Ini tentu mimpi buruk, bantahnya. Tak mungkin! Tidak mungkin Pek Hong Ing, isterinya tercinta, kini rebah di atas pembaringan itu dengan mata meram, bibir terkatup dan pakaian penuh darah yang sudah mengental. Tak mungkin!
Akan tetapi tetap saja pemandangan itu tidak berobah. Dia meloncat ke depan, berlutut di pinggir pembaringan untuk memandang lebih tegas lagi. Dirabanya pipi isterinya. Dingin! Tangannya ditarik kembali seolah-olah dia menyentuh api, ditatapnya lagi wajah isterinya, lalu diliriknya dada yang terluka bekas tusukan pedang.
Tiba-tiba dia menjerit dan semua orang yang berada di dalam kamar itu terjungkal, ada yang pingsan karena jerit itu mengandung kekuatan yang maha dahsyat. Tubuh pendekar itu terkulai, kepalanya diguncang keras-keras untuk mengumpulkan tenaga, dia memandang lagi, dirangkulnya mayat itu dan kini dia mengeluh, lalu merintih perlahan dan tubuhnya terkulai lemas, terjatuh pingsan di bawah pembaringan!
Gegerlah kamar itu. Geger dari mereka yang menolong orang-orang pingsan, dan ada pula yang menggotong tubuh Kun Liong, diletakkan di atas dipan di dalam kamar itu. Seperti mayat saja tubuh pendekar ini. Wajahnya sepucat wajah jenazah isterinya. Dadanya tidak bergerak seolah-olah napasnya sudah putus.
Giam Tun yang tadi tidak pingsan oleh jerit melengking tadi, hanya roboh terguling dan menggigil kini mendekati majikannya. Sebagai seorang ahli pengobatan dia tahu bahwa majikamya mengalami hantaman batin yang amat hebat. Dengan bercucuran air mata dia lalu mengambil obat dalam botol dan menggosok-gosokkan obat yang berbau keras itu di depan hidung majikannya. Semua orang memandang dengan terharu dan terutama kaum wanita tetangga mereka terisak-isak pilu.
Kun Liong berbangkis dan membuka matanya. Begitu siuman, dia memandang liar. Dan cepat dia bangkit duduk.
“Tidak mungkin! Hong Ing...!” Dia menoleh ke pembaringan dan meloncat. Berlutut di dekat jenazah isterinya. “Tidak mungkin! Sudah gilakah aku? Eh, Giam-lopek, sudah gilakah aku? Hong Ing mati? Tidak mungkin...!”
Dia memeluk isterinya, meraba-raba, dan memeriksa luka di ulu hati itu, luka yang menembus sampai ke punggung!
“Hong Ing... bagaimana ini...?”
“Taihiap.... harap tenangkan hati, taihiap...” Giam Tun berkata dengan suara gentar.
“Apa...? Tenang...? Keluarlah, harap semua keluar... biarkan aku sendirian berdua dengan isteriku!”
Giam Tun lalu memberi isyarat kepada semua tetangga untuk keluar. Mereka semua menanti di luar, tidak ada yang bicara, yang terdengar hanya isak tangis.
Setelah semua orang pergi, Kun Liong merangkul leher isterinya, menciumi muka yang sudah dingin itu, mengelus pipinya, dagunya, rambutnya sambil bercuran air mata.
“Hong Ing... isteriku... pujaanku... mengapa begini...? Mengapa...?”
Orang-orang di luar hanya mendengar suara pendekar itu puluhan kali mengajukan pertanyaan “mengapa” itu dan suara ini makin lama makin parau bercampur isak, membuat mereka menjadi terharu dan ikut pula menangis
Dengan pengerahan kekuatan yang amat hebat, barulah Kun Liong dapat menguasai dirinya. Lebih dari tiga jam dia menangisi mayat isterinya. Kemudian dia bangkit, lalu melangkah keluar, dan berdiri di pintu, seperti mayat hidup! Wajahnya menjadi pucat sekali tanpa ada bayangan darah, matanya sayu tanpa sinar, mulutnya seperti orang menahan rasa nyeri yang hebat dan dia seperti orang yang kehilangan ingatan, berdiri di luar pintu, dengan mata kosong memandang jauh melampaui orang-orang yang kumpul di situ.
“Taihiap...!” Giam Tun berseru dan maju berlutut.
Seruan ini menyadarkannya. Dia mengusap air matanya dengan punggung kepalan kedua tangannya, kanan kiri seperti seorang anak kecil kalau menangis. Khiu-ma menyeret sebuah kursi dan Kun Liong lalu menjatuhkan diri duduk di atas kursi itu.
“Paman Giam, Khiu-ma, ceritakanlah...! Tapi lebih dulu... mengapa aku tidak melihat Mei Lan menangisi jenazah ibunya?” Berkata demikian, air matanya kembali bercucuran.
Dengan suara meratap tangis, Khiu-ma berkata,
“Siocia juga telah pergi sejak malam tadi, entah kemana dan entah mengapa... tapi tentu dia yang menyebabkannya, dia yang membunuhnya... dia wanita yang tidak berperikemanusiaan itu...”
“Diamlah Khiu-ma!”
Giam Tun membentak wanita yang mulai histeris itu dan Khiu-ma menundukkan mukanya, terisak-isak.
“Kami berdua juga masih bingun memikirkannya, taihiap.”
Giam Tun mulai bercerita dan suaranya sudah tenang setelah dia melihat majikannya juga mulai tenang kembali.
“Ceritakan yang jelas sejak semula, apa yang telah terjadi. Dan saya minta dengan hormat kepada semua saudara sudilah menanti di ruangan depan agar saya dapat bicara dengan paman Giam Tun.”
Para tetangga itu mengundurkan diri, keluar dan memberi kesempatan kepada pendekar itu untuk mendengar penuturan Giam Tun karena mereka semua sudah mendengar persoalan itu.
Dengan panjang lebar dan jelas Giam Tun lalu menuturkan tentang kunjungan nyonya Lie Kong Tek, puteri dari ketua Cin-ling-pai malam tadi ketika baru saja toko ditutup.
“Kedatangannya aneh sekali, taihiap. Begitu datang dia marah-marah. Nyonya... eh, mendiang...” Giam Tun merasa lehernya tercekik ketika menceritakan nyonya majikannya.
“Paman Giam, kita harus dapat menghadapi kenyataan. Isteriku telah mati, kau bersikaplah tenang agar ceritamu jelas,” Kun Liong berkata dengan suara lirih.

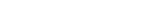











Komentar