DEWI MAUT JILID 018
“Hemm, Cia-kongcu. Hanya ada satu jalan, dan agaknya kalau kongcu sudah demikian memperhatikan nasib Yalima, tentu berarti kongcu mencintanya, bukan?”
Bun Houw terkejut bukan main seperti disengat ular berbisa. Hampir dia meloncat dari bangku yang didudukinya.
“Me... mencinta...?” teriaknya.
“Tentu kongcu mencinta anak kami.”
“Aku... aku tidak tahu... saya suka kepadanya dan kasihan, paman.”
“Begini, Cia-kongcu. Kalau kongcu mencintanya dan kongcu suka mengambilnya sebagai isteri, nah... biarlah saya akan membatalkan niat mempersembahkan dia kepada pangeran tua di Lhasa. Mempunyai mantu seperti kongcu juga sudah mengangkat derajat kami dan kelak kami harap kongcu dapat membantu kedua orang kakaknya itu.”
Bun Houw tercengang dan melongo seperti seekor monyet mendengar petasan.
“Ini... ini... saya tidak bisa memutuskan begitu saja, paman. Ini... ini adalah urusan penting yang harus disetujui orang tuaku dan... dan seujung rambutpun saya belum memikirkan untuk menikah...”
Kepala dusun itu menarik napas panjang.
“Kalau begitu, apa boleh buat... kami harus membawanya ke Lhasa.”
Bun Houw merasa diperas dan dia berkata dengan muka merah.
“Terserah kepada paman karena dia adalah puteri paman. Yalima tentu akan memaafkan saya karena saya sudah berusaha membujuk paman. Kalau paman berkeras hendak menjual puteri sendiri, saya tidak bisa melarang, hanya saya selamanya akan menganggap bahwa paman adalah seorang ayah yang amat keji! Selamat tinggal, paman.”
“Eh, nanti dulu, orang muda!” Kepala dusun itu berkata dan ikut bangkit pula. “Duduklah dulu dan jangan tergesa-gesa.”
Bun Houw duduk kembali karena sadar bahwa sikapnya terlampau kasar, hal ini terdorong oleh kecemasannya memikirkan nasib Yalima.
“Semua ucapan kongcu berkesan sekali di hati saya, karena merupakan hal yang baru pertama kali ini terjadi. Selamanya belum pernah ada orang menganggap seorang ayah berlaku keji terhadap puterinya yang dipersembahkan kepada pangeran! Dan juga baru sekarang ini ada orang luar berani mencampuri urusan antara ayah dan anak perempuannya. Baiklah kongcu. Selama kongcu menjadi sahabat kami dan sahabat puteriku Yalima, selama kongcu berada di sini, saya berjanji tidak akan mengantar Yalima ke Lhasa.”
Hati Bun Houw sudah sedemikian girangnya sehingga dia tidak mendengarkan dengan teliti. Dia meloncat dan merangkul kepala dusun itu, menepuk-nepuk pundaknya, bahkan hampir saja dia suka mencium pipi yang brewokan itu saking gembira hatinya.
“Terima kasih, paman. Terima kasih...!” katanya girang dan khawatir kalau-kalau kepala dusun itu akan menarik kembali janjinya yang tak disangka-sangkanya itu, dia segera berpamit dan kembali ke kuil.
“Suhu, teecu berhasil! Teecu berhasil!”
Kok Beng Lama memandang muridnya yang bersorak-sorak seperti anak kecil itu dengan mulut tersenyum. Tentu saja dia sudah tahu akan semua yang terjadi di rumah kepala dusun, karena sebetulnya muridnya mengunjungi ayah Yalima tadi, dia sudah lebih dulu menemui kepala dusun itu dan semua jawaban kepala dusun termasuk janjinya kepada Bun Houw adalah menurut petunjuknya yang ditaati sepenuhnya oleh kepala dusun itu!
“Bun How, cinta benarkah engkau kepada dara itu?”
Seperti tadi ketika mendengar perkataan tentang cinta dari kepala dusun, kini Bun Houw terkejut, bahkan lebih kaget daripada tadi karena yang berkata adalah suhunya. Seluruh mukanya berubah menjadi merah ketika dia mengangkat muka memandang wajah gurunya.
“Suhu... teecu suka dan kasihan kepada adik Yalima...”
“Itu tandanya cinta, maka engkau membelanya mati-matian.”
“Teecu tidak tahu, teecu tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan cinta, dan tentang pembelaan itu... andaikata Yalima itu seorang gadis lain yang mengalami nasib sama, hendak dipaksa diluar kehendaknya dipersembahkan kepada seorang pangeran tua, agaknya teecu juga akan membelanya. Apalagi dia yang selama ini menjadi sahabat baik teecu...”
Kok Beng Lama menghela napas.
“Pinceng mengerti, muridku. Akan tetapi, pembelaanmu ini tentu saja menimbulkan harapan-harapan di dalam hati keluarganya, dan di dalam hati dara itu sendiri.”
Bun Houw tidak mengerti dan menjawab seperti hendak membela diri,
“Dia menangis dan minta pertolongan teecu...”
“Sudahlah, Bun Houw. Memang sebaiknya kalau kau tidak jatuh cinta kepada dara itu, karena hal itu hanya akan mendatangkan keruwetan saja dalam hidupmu. Ah, agaknya engkau lupa bahwa waktu yang kita janjikan, yaitu lima tahun, telah lewat tanpa terasa oleh kita. Kurasa dalam hari-hari mendatang ini ayahmu akan datang untuk menjemputmu pergi dari sini.”
“Ohhh...! Sudah lima tahun?”
Bun Houw terkejut, akan tetapi juga girang. Betapa selama ini dia sering merindukan ayah bundanya, merindukan Cin-ling-san dan para anak murid Cin-ling-pai. Setelah kini dia hampir dapat melupakan kerinduannya karena kehidupan yang mulai menarik di Tibet, tahu-tahu lima tahun telah lewat dan dalam waktu singkat dia akan ikut ayahnya kembali ke Cin-ling-san!
“Aihh, teeeu senang tinggal di sini, suhu, dan teecu sedang berlatih dengan giat...”
“Muridku, ada waktunya berkumpul tentu akan tiba saatnya berpisah. Mengenai ilmu, semua ilmu yang kukenal telah kuberikan kepadamu, dan ditambah dengan ilmu yang kau pelajari dari ayahmu, kiranya engkau sekarang telah melebihi pinceng sendiri. Nah, kau bersiap-siaplah sebelum ayahmu tiba-tiba datang mengajakmu pergi agar engkau tidak menjadi kaget.”
Bun Houw pergi meninggalkan suhunya dengan perasaan tidak karuan rasanya. Ada rasa girang, akan tetapi juga ada rasa sedih meninggalkan tempat yang mulai disukanya itu. Dia naik ke puncak yang menjadi tempat kesukaannya itu dan duduk termenung di atas batu. Apalagi ketika tempat ini, mengingatkan dia kepada Yalima karena baru kemarin dara itu menangis dan menemuinya di tempat ini, seketika kegembiraannya untuk pulang ke Cin-ling-san lenyap.
Teringatlah dia sekarang mengapa Yalima menolak dan menangis ketika hendak dibawa pergi ke Lhasa oleh ayahnya, apa kata gadis itu? Bahwa Yalima tidak bisa meninggalkan tempat ini, tidak bisa meninggalkan dia! Dan sekarang tiba giliran dia yang harus pergi dan dia merasa betapa beratnya meninggalkan pegunungan ini, betapa beratnya meninggalkan Yalima!
“Houw-ko (kakak Houw)...!”
Bun Houw menengok dan tersenyum melihat Yalima berlari-lari naik ke puncak itu. Ketika tiba di depannya, seluruh wajah yang halus itu kemerahan dan napasnya terengah-engah karena dia tadi lari terus pada jalan yang mendaki.
Betapa segarnya sepasang pipi itu, kemerahan seperti digosok yanci. Betapa beningnya sepasang mata yang bersinar-sinar itu, bagian putihnya amat bersih dan manik hitamnya berkilauan. Dan mulut itu. Tersenyum lebar, segar kemerahan dan amat manisnya, dengan bibir basah dan penuh, terhias lesung pipit di sebelah kiri ujung mulut.
“Koko, terima kasih...” katanya dan langsung dia berlutut di depan Bun Houw sambil memegang tangan pemuda itu, digenggamnya erat-erat dengan kedua tangannya. “Terima kasih, Houw-ko. Engkau telah menghidupkan kembali Yalima!”
Bun Houw tersenyum. Rasa kebahagiaan yang aneh dan hangat menyelinap ke dalam hatinya, terasa benar olehnya. Dia membalas genggaman jari-jari tangan kecil itu dan berkata,
“Aku girang melihat engkau bergembira, Yalima adikku yang manis.”
Sambil mengguncang-guncang tangan Bun Houw karena gelora perasaannya, dara itu bercerita,
“Aku mendengarkan semua percakapan antara engkau dan ayah! Aku bersembunyi di balik bilik itu dan tahukah apa yang menjadi keputusanku di saat itu? Kalau engkau tidak berhasil, kalau ayah bersikeras memaksaku, aku akan bunuh diri!”
“Aihh, moi-moi...!”
“Benar, koko. Akan tetapi ketika mendengar ayah akhirnya berjanji padamu tidak akan membawaku ke Lhasa, hampir aku berteriak-teriak saking senangku, akan tetapi aku tidak berani berteriak dan aku hanya menari-nari saja. Ahh, Houwko... engkau membikin aku bahagia sekali, sampai mati aku tidak akan melupakan pertolonganmu, koko!”
Terdorong oleh gelora hatinya yang penuh kelegaan dan kebahagiaan, merasa telah terlepas dari ancaman yang amat mengerikan baginya, Yalima lalu membawa tangan pemuda yang digenggamnya itu ke depan mukanya, dibelainya dengan hidung, bibir, dan pipinya.
Jantung Bun Houw berdebar keras, tangannya yang diciumi oleh dara itu menjadi gemetar dan dia cepat-cepat menarik tangannya, lalu merangkul sehingga Yalima rebah di atas dadanya dan tidak dapat lagi menciumi tangannya. Yalima seperti tidak bertulang lagi, begitu lemas dan lunak rebah di atas dadanya, kepalanya bersandar di atas dada dan kedua lengan Bun Houw tanpa disengaja memeluk pinggangnya.
Yalima juga melingkarkan kedua lengan di atas lengan pemuda itu, memegangi tangannya seolah-olah tidak ingin kedua lengan pemuda itu terlepas lagi dari rangkulan pada punggungnya. Duduk seperti itu, bersandar di dada dan dipeluk pinggangnya, mendatangkan rasa aman dan nyaman, dia merasa seperti terayun-ayun di antara gumpalan awan putih di langit biru, begitu penuh damai, tenteram bahagia dan bebas dari segala ancaman.
Yalima memejamkan matanya, takut kalau-kalau yang dialaminya ini hanya mimpi lagi saja seperti yang terlalu sering dia mimpikan, dia tidak ingin pengalaman ini, biar dalam mimpi sekalipun, untuk berakhir, ingin rebah seperti itu selama hidupnya!
Sampai lama dua orang muda itu duduk seperti itu. Bun Houw di belakang, Yalima di depan setengah rebah di dadanya, kedua lengannya melingkari pinggang yang amat kecil itu dan jari-jari tangan Yalima tergetar-getar dan halus seperti anak-anak ayam yang baru menetas, hinggap di atas kedua tangannya.
Juga Bun Houw memejamkan matanya, tenggelam timbul di antara kenikmatan dan kesungkanan, dibuai oleh gelora hatinya sendiri. Getaran-getaran aneh di tubuhnya membuat Bun Houw merasa cemas juga, dan dia mengambil keputusan untuk memecahkan kesunyian yang nikmat namun mencemaskan itu dengan kata-kata yang keluar agak tersendat dan gemetar.
“Moi-Moi, aku...dapat merasakan kedukaanmu ketika hendak pergi, karena... akupun merasa demikian... setelah diingatkan suhu bahwa akupun akan pergi dari sini...!”
Jerit halus meluncur keluar dari mulut Yalima dan dengan gerakan cepat seperti seekor ular dia membalikkan tubuhnya menghadapi Bun Houw. Demikian cepat gerakannya sehingga kedua lengan Bun Houw masih melingkari pinggangnya dan kini kedua tangan dara itu mencengkeram dada baju Bun Houw, mukanya begitu dekat hampir bersentuhan dengan muka Bun Houw dan kedua matanya memandangi penuh selidik dan penuh kecemasan seperti mata seekor kelinci yang ketakutan dikejar harimau.
“Apa katamu, koko? Kau... kau mau pergi...? Pergi meninggalkan tempat ini, meninggalkan...aku...?” Suaranya tersendat-sendat, muka yang tadi kemerahan dan berseri itu kini menjadi pucat.
Bun Houw merasa betapa kecemasan hebat terbawa oleh pertanyaan itu, dan begitu dekatnya muka dara itu sehingga hembusan napasnya dan hawa ketika berkata-kata itu terasa meniup pipinya dengan halus. Dia hanya mengangguk, akan tetapi anggukan ini datang seperti palu godam menghantam kepala Yalima.
“Houw-ko... eh, Houw-ko, aku ikut...! Kalau kau pergi, bawalah aku, Houw-ko... biar aku akan menjadi pelayanmu, menjadi budakmu, menjadi apa saja... akan tetapi bawalah aku bersamamu...”
Melihat sepasang mata lebar dan indah itu terbelalak penuh kecemasan, hidung yang kecil mancung itu kembang kempis cupingnya seperti mau menangis, mulut yang mungil dengan bibir yang merah basah itu tergetar dan gigi-gigi kecil putih seperti mutiara menggigit bibir bawah yang merah penuh seolah-olah mudah pecah itu untuk menahan tangis, Bun Houw merasa terharu sekali.

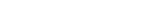











Komentar