DEWI MAUT JILID 016
Seluruh daerah Negara Tibet merupakan pegunungan yang sambung-menyambung, pegunungan yang tinggi dan luas sekali dengan Pegunungan Himalaya sebagai benteng yang panjang dan menjulang tinggi di perbatasan selatan. Ibu kota atau kota rajanya adalah Lhasa dimana terdapat istana kerajaan dan golongan yang paling berkuasa di sana adalah para pendeta Lama.
Karena seperti lajimnya di dunia ini, yang berkuasa tentu memperoleh kedudukan tinggi dan mulia, maka tentu saja terjadi perebutan kekuasaan di antara para pendeta Lama sehingga terjadilah pemecahan dan terbentuklah golongan-golongan yang kadang-kadang saling bertentangan untuk memperoleh kekuasaan.
Pada waktu itu, yang berkuasa di samping raja adalah para pendeta Lama golongan Jubah Kuning dan kedudukan mereka sedemikian kuatnya sehingga tidak ada golongan lain yang berani memberontak.
Beberapa puluh li jauhnya dari Lhasa, di sebelah selatan, dimana sungai yang mengalir memasuki sungai besar Yalu-cangpo, terdapat sebuah kuil besar. Dahulu kuil ini menjadi pusat dari gerakan Lama Jubah Merah yang pernah memberontak akan tetapi berhasil dibasmi oleh pasukan Tibet yang dibantu oleh Pemerintah Beng (baca cerita Petualang Asmara). Kini para Lama Jubah Merah masih ada, namun mereka tidak lagi aktip dan hidup dengan penuh tenteram dan damai, bertani dan tekun hidup sebagai pertapa yang saleh.
Ketua dari para Lama yang jumlahnya hanya tinggal dua puluh orang lebih ini adalah seorang yang memiliki kesaktian luar biasa dan bernama Kok Beng Lama. Di dalam cerita Petualang Asmara telah diceritakan bahwa Kok Beng Lama ini adalah ayah kandung dari Pek Hong Ing isteri dari Pendekar Sakti Yap Kun Liong.
Usia pendeta Lama ini sudah delapan puluh tiga tahun namun tubuhnya masih sehat, kokoh kekar dan tinggi besar seperti raksasa. Karena ketuanya tidak mempunyai keinginan sesuatu, maka semua anggauta Lama Jubah Merah juga tidak menginginkan sesuatu kecuali hidup aman tenteram dan sehat di lembah pegunungan dekat sungai yang tanahnya subur itu.
Melihat betapa Kok Beng Lama hanya tekun melatih ilmu kepada murid tunggalnya, maka para Lama itupun terbawa-bawa, tekun melatih ilmu-ilmu mereka yang memang sudah tinggi sehingga kepandaian mereka menjadi makin masak.
Murid tunggal dari Kok Beng Lama ini adalah Cia Bun Houw, putera dari Pendekar Sakti Cia Keng Hong ketua Cin-ling-pai. Semenjak berusia lima belas tahun, tepat seperti telah dijanjikan oleh Cia Keng Hong dan isterinya, maka Bun Houw dikirim ke tempat sunyi ini untuk belajar ilmu dari Kok Beng Lama selama lima tahun.
Perjanjian ini diadakan ketika Bun Houw diculik oleh para Lama yang dulu memberontak kepada Pemerintah Tibet (baca cerita Petualang Asmara). Dengan amat tekunnya pendeta itu menurunkan ilmu-ilmunya yang paling tinggi, hasil penggemblengan ayah bundanya yang sakti di Cin-ling-pai. Pemuda itupun amat suka akan ilmu silat, maka diapun rajin sekali berlatih sehingga dengan mudahnya semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya dapat dia terima dan kuasai dengan mudahnya.
Tanpa terasa, lima tahun telah hampir lewat selama Bun Houw hidup di tempat sunyi itu. Namun dia tidak merasa kesunyian karena dia diberi kebebasan secukupnya oleh gurunya, bahkan dia diperkenankan mengunjungi dusun-dusun di sekitar tempat itu sehingga dia dapat berhubungan dengan rakyat Tibet yang cara hidupnya aneh dan asing baginya. Berkat pergaulan ini, sebentar saja Bun Houw sudah pandai berbahasa Tibet dan setelah tinggal di situ selama lima tahun, dia telah mempunyai banyak kenalan dan sahabat.
Kini Cia Bun Houw telah menjadi seorang pemuda berusia dua puluh tahun. Karena ayahnya dan ibunya dahulu terkenal sebagai pria yang tampan dan wanita yang cantik sekali, maka tidaklah mengherankan apabila pemuda ini memiliki bentuk tubuh yang gagah dan wajah yang tampan pula. Dan berbeda dengan watak encinya, Cia Giok Keng, yang galak dan keras hati, sebaliknya watak pemuda in halus dan manis budi, romantis dan sama sekali tidak suka akan kekerasan! Agaknya watak ini terbina karena dia hidup selama lima tahun di tengah-tengah para Lama yang hidup penuh damai itu, dan pergaulannya dengan rakyat Tibet yang masih jujur, polos dan wajar sikapnya dalam cara hidupnya sehari-hari.
Bun Houw suka akan segala yang indah-indah, dia dapat menikmati keindahan alam sampai berjam-jam tanpa bosan, melihat keindahan matahari terbit atau matahari terbenam, melihat keindahan kembang-kembang dan duduk termenung di pinggir sungai melihat air mengalir tiada hentinya sambil berdendang gembira
Kegagahannya, ketampanannya, dan kemanisan budinya itu tentu saja membuat semua orang suka kepadanya, terutama sekali dara-dara Tibet yang berwatak polos dan wajar. Diam-diam banyak sekali dara Tibet yang jatuh cinta kepada Bun Houw.
Akan tetapi Bun Houw bersikap manis kepada mereka semua, dan terutama sekali kepada seorang dara puteri ketua dusun yang bernama Yalima, seorang dara berusia lima belas tahun, cantik rupawan seperti setangkai bunga teratai ungu. Demikian cantik dan selalu gembira dara ini sehingga Bun Houw merasa suka sekali kepada Yalima, dan seringkali dua orang muda ini berjalan-jalan, bersenda-gurau, bahkan Bun Houw berkenan mengajarkan ilmu silat sekedarnya kepada dara ini.
Atas permintaan Bun Houw, dara Tibet ini menyebutnya koko (kakak) sedangkan dia sendiri menyebut moi-moi (adik) kepada dara itu. Mereka masing-masing saling mengajar Bahasa Han dan Tibet, dan berkat bantuan dara inilah maka Bun Houw pandai bicara dalam Bahasa Tibet dengan lancar sedangkan Yalima, biarpun dapat juga mengerti Bahasa Han, namun dia hanya dapat mengucapkan kata-kata Han dengan kaku dan lucu.
Tidak pernah ada sepatahpun kata cinta keluar dari mulut kedua orang muda ini, namun tidak saling berjumpa dua tiga hari saja mereka merasa tersiksa dan rindu!
Pada suatu senja, ketika Bun Houw sudah lelah berlatih ilmu pedang dan duduk beristirahat seorang diri di tempat yang disukainya, yaitu di sebuah puncak dari mana dia dapat menyaksikan matahari terbenam, pemuda ini termenung dan tenggelam ke dalam keindahan pemandangan alam yang dihadapinya.
Jauh di balik puncak-puncak gunung di barat, matahari terbenam meninggalkan cahaya merah, kuning, biru yang luar biasa indahnya. Gumpalan-gumpalan mega dan awan yang biasanya berwarna kehitaman dan putih, kini terbakar oleh cahaya matahari itu menimbulkan percampuran warna sehingga terciptalah segala macam warna di dunia ini, terlukiskan di langit yang biru muda.
Gumpalan-gumpalan awan itu menciptakan bermacam bentuk yang berubah-ubah dan bergerak perlahan, hampir tidak dapat diikuti pandangan mata sehingga bentuk-bentuk itu tahu-tahu berobah. Warna yang tidak menyilaukan mata, sedap dipandang dan amat berkesan di dalam hati. Keindahan yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan keindahan matahari terbenam di waktu kemarin atau yang sudah-sudah karena memang tidak pernah sama. Keindahan yang hidup, tidak mati seperti lukisan tangan manusia.
“Koko...!”
Suara itu dikenalnya seketika. Siapa lagi yang memiliki suara merdu jernih seperti itu, yang menyebut kata “koko” dengan tekanan suara dan nada seperti itu kalau bukan Yalima? Suara yang merupakan keindahan baru bagi telinga, dan ketika dia menoleh dan memandang, agaknya keindahan alam di waktu matahari terbenam itu masih kalah indahnya oleh dara yang kini berdiri di depannya.
Akan tetapi, mendadak Bun Houw meloncat bangun dan memandang dengan kaget dan heran. Wajah yang biasanya segar, dengan sepasang pipi merah muda, sepasang mata bersinar-sinar, bibir merah basah yang tersenyum manja penuh tantangan terhadap kehidupan, kini tampak layu dan tidak bersinar lagi, biarpun masih seindah matahari terbenam!
“Moi-moi! Ada apakah...?” tanyanya sambil meloncat mendekat dan memegang tangan yang halus kulitnya akan tetapi agak kasar telapak tangannya karena setiap hari harus bekerja berat itu.
Mendengar pertanyaan orang yang selalu dikenangnya ini, tiba-tiba Yalima menangis sesenggukan dan menyembunyikan mukanya di dada Bun Houw! Sejenak Bun Houw menengadah dan memejamkan matanya. Aneh rasanya! Baru sekali ini dia begitu dekat dengan Yalima, biarpun hampir setiap hari mereka bercanda. Dara ini merangkul pinggangnya dan mendekapkan muka pada dadanya, terisak menangis dengan penuh kesedihan.
Bun Houw menekan jantungnya yang berdebar tegang, kini kekhawatiran menguasai hatinya dan melupakan ketegangan yang aneh itu. Tangannya mengusap rambut yang hitam halus dan amat panjang, dikuncir menjadi dua itu. Diusapnya rambut di kepala yang berbau harum bunga itu.
“Aih, moi-moi, tenangkanlah hatimu dan ceritakan apa yang terjadi maka engkau yang belum pernah kulihat menangis menjadi begini berduka. Ceritakanlah dan aku pasti akan menolongmu.”
Mendengar ucapan ini, Yalima melepaskan rangkulan kedua lengannya pada pinggang pemuda itu dan melangkah mundur. Mukanya menjadi merah sekali, matanya juga agak merah dan air mata membasahi kedua pipinya, juga baju dalam Bun Houw menjadi basah. Sepasang alis kecil hitam melengkung indah seperti dilukis itu agak berkerut, akan tetapi terkilas di pandang matanya sikap yang agak canggung dan malu, agaknya baru teringat olehnya betapa tadi dia memeluk pemuda itu dan mendekap begitu erat.
Bun Houw menuntun tangan dara itu duduk di atas batu-batu licin bersih yang sering mereka pergunakan sebagai bangku-bangku di waktu mereka bercakap-cakap dan bersendau gurau di situ. Bun Houw mengeluarkan sehelai saputangan bersih dan kering dari sakunya karena dara itu memegang saputangan yang sudah basah semua.
“Keringkanlah air matamu dan hidungmu!” katanya tersenyum menghibur.
Yalima menerima saputangan itu, menyusut air matanya, juga hidungnya karena di waktu menangis tadi, bukan hanya matanya yang mengeluarkan air, melainkan juga hidungnya. Tanpa malu-malu karena memang mereka sudah akrab, Yalima menyusut hidungnya yang kecil mancung, kemudian dia mengembalikan saputangan yang menjadi basah itu akan tetapi sebelum Bun Houw menerimanya, dia sudah menariknya kembali dan berkata, suaranya agak parau karena tangis,
“Biar kucuci dulu!”
“Ahh, mengapa pula kau ini? Tidak usah dicuci juga tidak apa!” Bun Houw mengambil kembali saputangannya dan memasukkannya ke dalam saku bajunya.
“Terima kasih...” dara itu berkata, menyedot hidungnya dan menahan isak.
“Moi-moi, apakah yang terjadi? Kau mengejutkan hatiku benar.”
“Koko, benarkah engkau akan menolongku?”
“Tentu saja!”
Gadis cilik itu menggelengkan kepalanya dengan muka sedih.
“Tidak mungkin, koko. Kau tidak akan bisa menolongku.”
“Ceritakanlah dulu apa persoalannya, jangan kau mudah putus harapan.”
Dara itu memandang wajah Bun Houw, lalu tiba-tiba dia memegang tangan pemuda itu, dikepalnya tangan kanan pemuda itu dengan jari-jari kedua tangannya yang kecil, diguncangnya dan didekapnya sekuat tenaganya ketika dia berkata,
“Koko, kau tolonglah aku, tolonglah aku! Ayah hendak membawaku ke Lhasa!”
Bun Houw memandang aneh.
“Ah, mengapa engkau minta tolong? Bukankah sudah sering engkau diajak ayahmu ke Lhasa?”
“Akan tetapi sekali ini untuk selamanya, koko. Aku tidak akan kembali kesini lagi.”
“Eh? Mengapa begitu?”
“Aku... aku... akan dihaturkan kepada seorang pangeran...” Gadis itu kembali terisak dan memandang Bun Houw dengan mata basah. “Koko, kau tolonglah aku... akan tetapi... bagaimana mungkin... ahh, bagaimana baiknya, koko?”
Bun Houw memegang kedua pundak dara itu sambil tersenyum.
“Engkau ini aneh sekali, moi-moi. Setiap orang wanita di daerah ini tentu akan menceritakan berita ini sambil tertawa-tawa penuh bahagia. Bukankah setiap wanita, terutama setiap orang gadisnya di daerah ini selalu mengharapkan agar dapat dihaturkan kepada seorang pangeran yang berkuasa di Lhasa? Kau akan berganti pakaian indah setiap hari, tidak usah bekerja di sawah dan bekerja berat, berenang di atas uang dan perhiasan, terhormat dan senang...”
“Aku tidak mau! Aku tidak suka!”

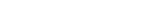











Komentar